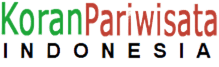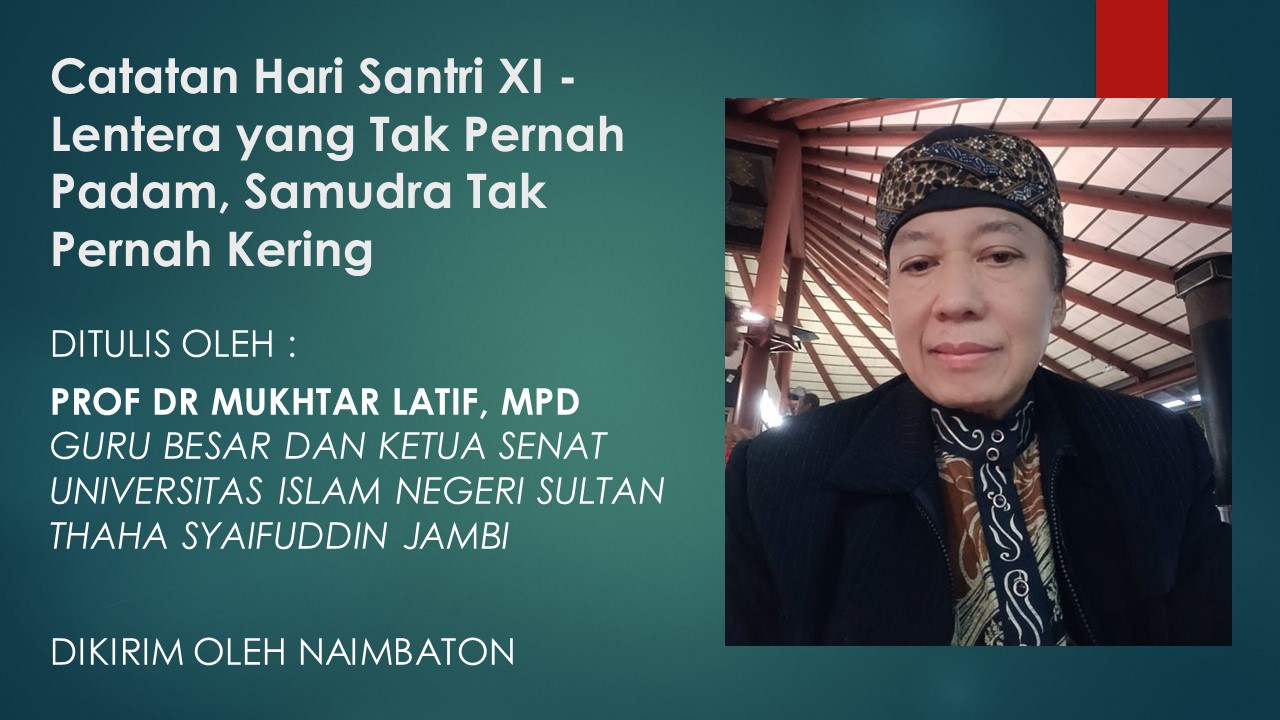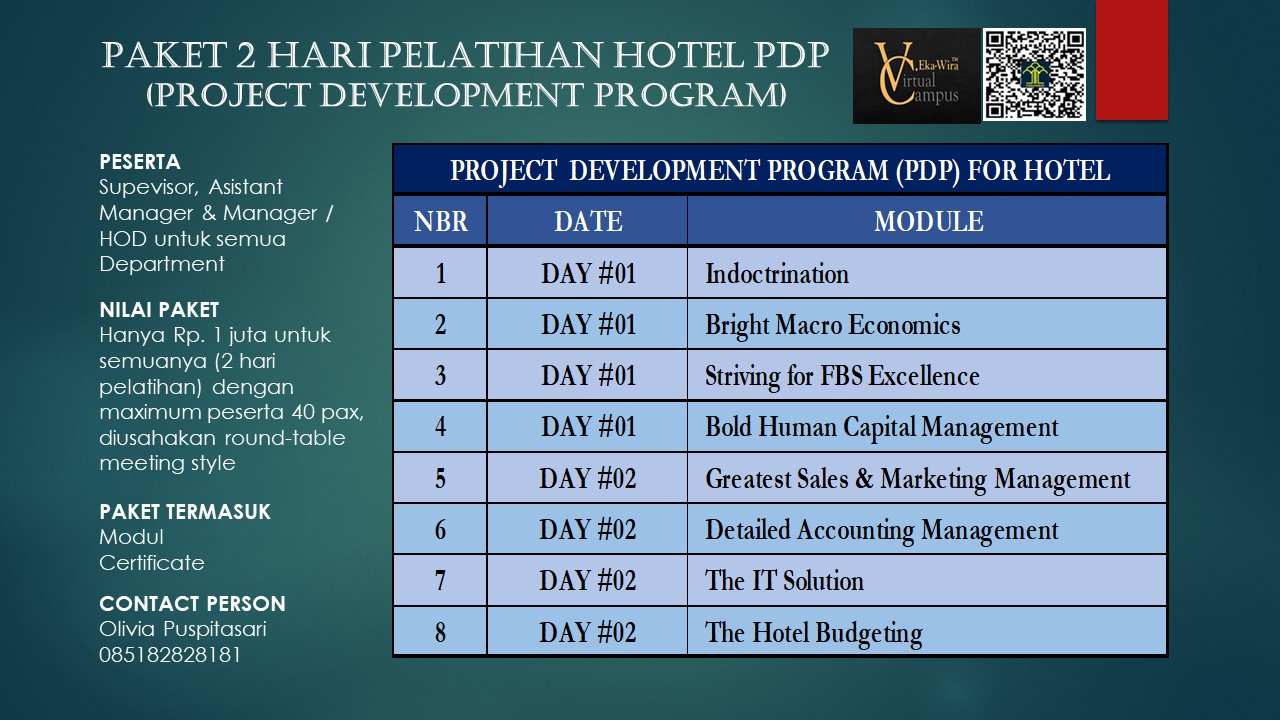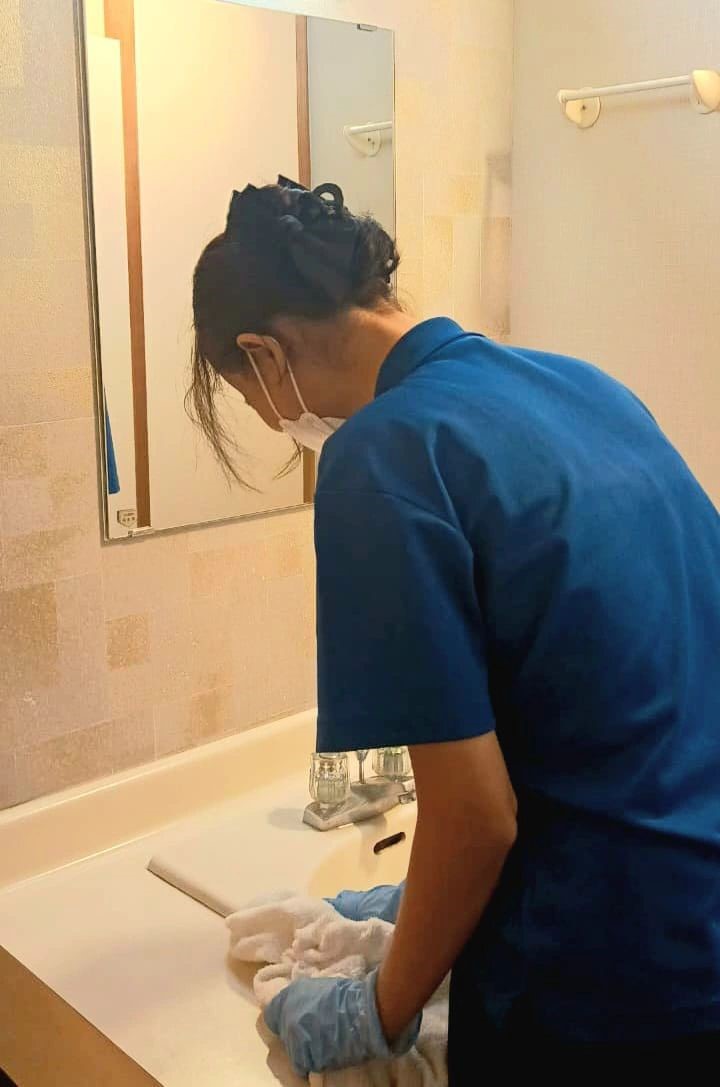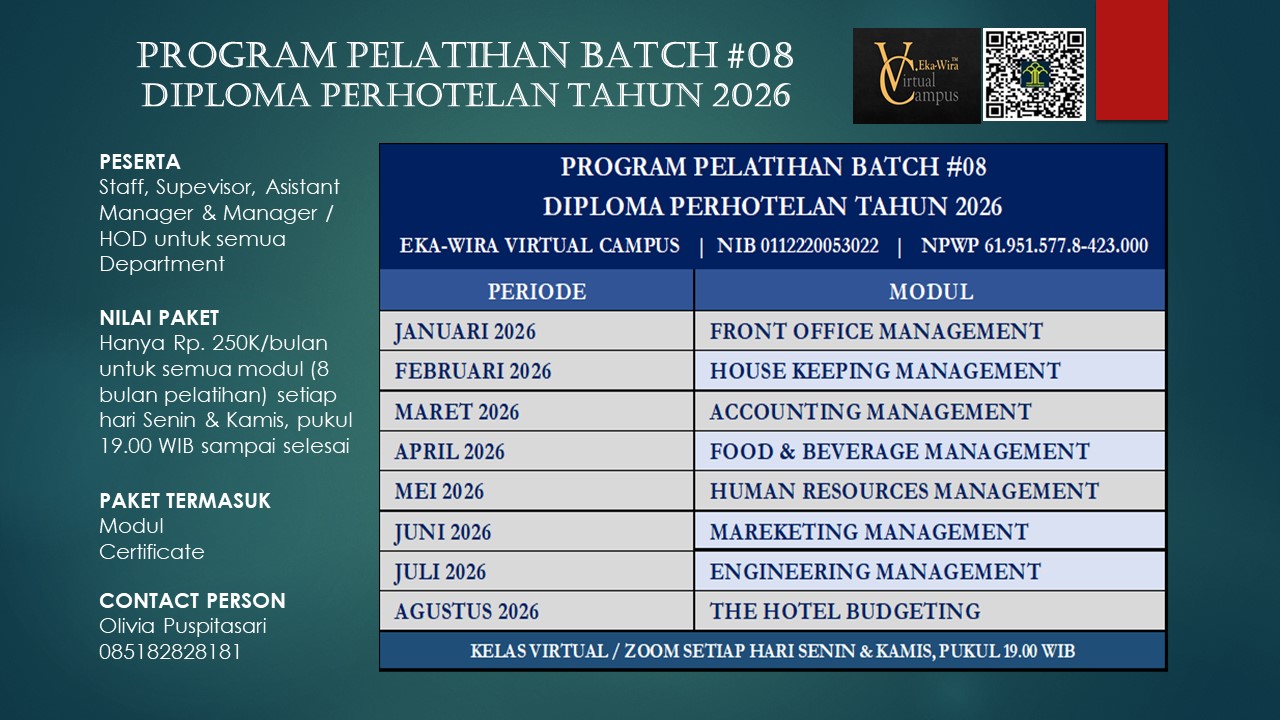Catatan Hari Santri XI 22 Oktober 2025, Lentera yang Tak Pernah Padam, Samudra Tak Pernah Kering
Oleh : Prof Dr Mukhtar Latif, MPd
(Guru Besar dan Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi)
Pendahuluan
Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 bukan sekadar rutinitas seremonial. Peringatan HSN merupakan penanda sejarah sekaligus check-point (nilai tambah) refleksi kebangsaan.
Jika kita ibaratkan, pesantren dan santri adalah lentera yang tak pernah padam menjaga warisan keilmuan Islam-Nusantara dan samudra yang tak pernah kering menyumbangkan ksatria-ksatria sejati bagi Ibu Pertiwi (Amin, 2018, hlm. 45). Sejak era pergerakan hingga era Gen Z saat ini, peran santri tak pernah luput dari narasi utama pembangunan umat dan bangsa.
Momentum HSN XI tahun 2025 ini harus menjadi titik tolak menegaskan kembali posisi sentral santri. Santri bukan bukan hanya pewaris tradisi, melainkan juga arsitek masa depan peradaban. Jati diri santri yang ditempa oleh disiplin (sin: satrul al-‘awrah), keilmuan (nun: naibul ulama) dan moralitas (ta’: tarkul ma’ashi) pada hakikatnya merupakan cerminan jati diri kolektif umat dan bangsa Indonesia yang majemuk namun religius (Asy’ari, 2020, hlm. 120). Santri terus bertransformasi, mulai dari benteng pertahanan negara hingga menjadi agen perubahan di tengah hiruk-pikuk disrupsi digital.
Untuk memahami jati diri santri, kita perlu kembali ke akarnya. Secara etimologi, kata “santri” memiliki banyak interpretasi, mulai dari yang berasal dari bahasa Sanskerta Sasstri (orang yang tahu ilmu kitab suci) hingga akronim Arab yang populer di kalangan pesantren. Namun, secara sosiologis-historis, santri adalah pelajar yang tinggal di pondok (pesantren) dan berjuang untuk menghidupi ajaran para kiai yang sanad keilmuannya tersambung hingga Rasulullah (Siraj, 2021, hlm. 78).
Sejarah mencatat bahwa pesantren (bersama santri di dalamnya) adalah episentrum (pusat) perlawanan. Di masa penjajahan, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga benteng pertahanan moral dan militer (Dhofier, 2017, hlm. 201). Puncak historis peran santri terwujud dalam Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini bukan hanya legitimasi agama, tetapi juga mobilisasi total yang menjadi penyulut heroik Pertempuran 10 November di Surabaya (Fealy & Bubalo, 2016, hlm. 15).
Setelah kemerdekaan, peran santri bergeser menjadi pembangun dan penjaga nilai. Pesantren menjadi lembaga yang menjaga keseimbangan antara tradisi (ilmu salaf) dan modernitas (ilmu khalaf). Kini, di era digital, pesantren dan santri tidak lagi pasif. Mereka aktif mengintegrasikan teknologi untuk dakwah dan pengembangan ekonomi, membuktikan bahwa Kitab Kuning tidak alergi terhadap kode digital (digital code) (Bruinessen, 2022, hlm. 115).
Dinamika Umat
Dinamika umat dan bangsa Indonesia selalu berjalan seiring dengan denyut nadi pesantren. Di arena politik, peran santri tidak bisa diremehkan. Sejak awal kemerdekaan, tokoh-tokoh santri terlibat langsung dalam perumusan dasar negara, memastikan nilai-nilai keislaman terakomodasi secara harmonis dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945 (Barton, 2024, hlm. 88).
Namun, kontribusi terbesar santri justru ada di ranah sosial-kultural. Pesantren merupakan pabrik nilai yang secara konsisten mencetak generasi yang memegang teguh wasathiyyah Islam, yaitu moderasi beragama. Mereka adalah garda terdepan dalam merawat toleransi dan menolak radikalisme (Muttaqin, 2023, hlm. 501).
Prinsip kiai, “Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik” (al-muhafazhatu ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah)” menjadi landasan bagi santri untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Nilai-nilai seperti tawadhu (rendah hati) dan khidmah (pengabdian) yang ditanamkan di pondok, menjelma menjadi etos kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan umat (Mustofa, 2021, hlm. 590). Intinya, santri adalah penyeimbang, jembatan yang menghubungkan antara keteguhan tradisi dan kebutuhan kemajuan.
Era Digital
Ketika dunia berputar pada poros digital, santri justru menunjukkan adaptasi yang elegan. Polemik klasik tentang “Kitab Kuning versus Gadget” kini harus diselesaikan dengan sintesis yang cerdas. Santri hari ini adalah mereka yang mampu membaca Kitab Kuning, warisan keilmuan klasik dari ulama salaf, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkannya.
Bagi mereka, digitalisasi bukanlah ancaman, melainkan perpanjangan tangan dakwah (Nurhayati, 2022, hlm. 50). Ribuan kitab fiqih, tafsir, dan hadis yang tadinya hanya bisa diakses dalam wujud manual, kini tersedia dalam aplikasi di ponsel pintar. Hal ini tidak mengurangi kedalaman ilmu, tetapi justru memperluas akses dan mempercepat proses belajar (tafaqquh fiddin).
Namun, digitalisasi ini hanya alat. Yang membedakan santri adalah bimbingan langsung (musyafahah) dari kiai dan sanad keilmuan yang kuat, sehingga mereka tidak tersesat dalam lautan informasi yang dangkal. Santri menggunakan teknologi untuk mengabadikan dan mendistribusikan turāth (warisan keilmuan) mereka, bukan untuk menggantikannya. Inilah cara santri membuktikan bahwa tradisi bisa berdialog mesra dengan teknologi.
Santri Gen Z
Santri yang kini mendominasi bangku pondok adalah bagian dari Generasi Z. Sebuah generasi yang lahir dan bernapas di tengah konektivitas internet. Untuk menjadi penerus ulama (naibul ulama) sekaligus pemimpin umat (ra’isul ummah) di masa depan, ada beberapa kompetensi krusial yang harus disemai.
Pertama, Literasi Digital dan Etika Digital. Santri Gen Z harus menjadi “filter” sekaligus “penyebar”. Mereka harus cakap memilah informasi (melawan hoax dan radikalisme digital) dan piawai menyajikan konten dakwah yang sejuk dan relevan (Qomaruddin, 2024, hlm. 102).
Kedua, Keterampilan Soft Skill Lintas Disiplin. Pondok harus membekali santri dengan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif. Di era yang kompleks, problem solving yang dilandasi nilai fiqh adalah aset tak ternilai (Ansori, 2023, hlm. 35).
Ketiga, Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship). Di tengah persaingan ekonomi global, santri tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus menjadi subjek yang mandiri. Melalui pengembangan unit usaha pesantren dan ekonomi syariah, santri diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menopang kemandirian umat (Latif, 2021, hlm. 285). Tujuannya sederhana, mencetak pemimpin umat yang berakal modern, berjiwa pesantren.
Penutup
Peringatan HSN XI tahun 2025 ini menjadi penegasan bahwa jati diri santri merupakan fondasi ketahanan moral dan spiritual bangsa. Dari semangat Resolusi Jihad hingga adaptasi di era streaming dan AI, santri membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan transformatif yang tak pernah berhenti berjuang.
Jati diri santri adalah komitmen untuk terus belajar (tholabul ilmi), berbakti (khidmah) dan menjadi pelopor kebaikan (sābiqul khair). Di tengah derasnya arus globalisasi, mereka adalah jangkar yang menjaga Indonesia tetap tegak, damai, dan berkarakter. Selamat Hari Santri, teruslah menjadi lentera keilmuan dan samudra kearifan. Jati dirimu adalah jati diri umat dan bangsa. (Berbagai Sumber).